Terpaksa Mengamini Pilihan Erika
Lagi- lagi, Adele.
“Kayaknya kita dikutuk, nih. Di mana-mana diikutin sama
Adele,” kataku, enggak lama setelah mendengar suara Adele dari speaker restoran. Dan kamu hanya
membalasnya dengan senyuman. Lalu pandanganmu kembali pada sekeranjang burger
dan kentang. Aku, mulai terganggu dengan suasana hening diiringi lagu All I Ask.
“Aku..”
“Aku.. eh, kenapa?”
“Kamu duluan aja, kenapa?”
“Enggak, ini burgernya gede banget. Aku simpen buat nanti
aja setengah,” kataku sambil membungkus burger dan meringis malu. Sambil
berpikir apakah aku harus pura-pura enggak peduli dengan sisanya dan
meninggalkan di meja? Atau jadi diri sendiri saja dan membawanya pulang? Ah,
aku pikir pilihan kedua saja.
“Aku jahat, yah?” tanyamu ketika aku masih sibuk memikirkan
apakah pilihanku benar.
“Eh?”
“Iya, aku jahat yah selama ini?”
“Emm.. Ada apa, sih ini?”
“Aku merasa jahat aja selama ini sama kamu.”
“Okee.. kamu mengulang kata jahat tiga kali.”
“Okee.. kamu mengulang kata jahat tiga kali.”
“Aku serius. Aku merasa efek keberadaan aku buat kamu,
enggak bagus. Gitu. Kan?”
“Kok, gitu?”
Tiba-tiba aku ingat di mana lokasi tenggorokanku. Dan aku
merasa ada seutas tali melingkarinya, ditarik kedua ujungnya, memblokir semua
asupan udara ke paru-paru. Sementara jantungku berdetak lebih kencang dari seharusnya.
Kalau restoran ini tidak dipenuhi suara Adele, sudah pasti dentuman jantungku
akan sampai ke telinga semua pengunjung lainnya. Kamu tak menjawab. Aku diam
dalam rasa panik mendalam. Tarik napas
dalam, buang. Pikirku. Kulakukan. Tiga kali, baru aku merasa lebih tenang.
“Justru kamu alasan aku bangun pagi,” kataku pelan.
“Tapi aku juga yang membuat kamu tidur larut,” jawabmu
tajam.
“Jadi, maksud kamu apa? Kamu pengen aku bilang kamu jahat?”
“Iya. Karena memang begitu kenyataannya. Aku cuma ngasih
kamu harapan yang enggak berujung pada kenyataan. Dan aku selalu membuat kamu
berputar-putar di dalam lingkaran. Aku tahu. Aku harap enggak begitu, tapi
kenyataannya begitu. Simple. Jangan
bilang harapan itu ada artinya. Karena memang enggak. Untuk orang kayak kita,
enggak ada artinya punya harapan yang melebihi apa yang bisa kita punya. Dari
semua orang, aku pikir kamu orang yang paling paham soal ini. Kamu enggak naïf. Tapi untuk hal yang satu ini,
kamu, membiarkan aku untuk enggak masuk akal, dan aku juga membiarkan diri aku
sendiri mencari-cari jalan yang mungkin bisa memperpanjang, bukannya menemukan
jawaban atau….”
“Atau menggali lubang untuk keluar?”
Kamu hanya mengangguk. Sementara aku mulai kehilangan rasa atas
kedua kakiku. Apakah mereka masih menginjak tanah? Atau melebur? Seperti ada
pasir hisap di kedua ujung jari kakiku dan tidak lama, mereka akan mulai
menelanku bulat-bulat. Lalu aku menghilang. Seperti semua harapan yang sudah
aku simpan selama ini yang seketika menghilang bersama semua yang kau ucapkan.
Aku meresapi kata-katamu. Aku berharap aku enggak paham. Sayangnya, bukan
seperti itu kisah hidupku. Aku selalu paham. Sehingga aku selalu harus memilih.
Dan seringkali, pilihanku tak mendapatkan dukungan.
“Kamu tahu kapan pertama kali aku berharap dilahirkan
sebagai laki-laki?” tanyaku tanpa mengharap jawaban. “Waktu aku masih TK. Aku
pengen main sepeda sama teman-teman, yang kebanyakan laki-laki. Lalu aku
dilarang, ketika aku tanya kenapa, ibu hanya menjawab karena aku perempuan. Aku
ingat betapa aku enggak paham saat itu, karena jawaban itu enggak masuk akal.
Aku punya sepeda. Teman-temanku semua main. Kebetulan, teman-temanku saat itu
banyak laki-laki. Tapi walau aku menangis, aku enggak boleh main sepeda
jauh-jauh. Aku hanya boleh menaikinya di lapangan dekat rumah. Itu pertama kali
aku begitu membatin, seandainya aku dilahirkan laki-laki, aku pasti lebih
bebas,” sampai akhir kisah, aku pun tetap memandang gelas dan sedotan. Kalaupun
kau tertidur aku tidak akan tahu. Tapi, entah kenapa aku yakin kau menyimak
benar.
“Kali kedua, aku berharap dilahirkan sebagai laki-laki,
waktu SMA. Ketika teman-teman laki-laki sibuk menyatakan cinta. Atau melakukan
sesuatu untuk orang yang disukainya. Aku merasa sebagai perempuan, hanya bisa
menunggu. Bahkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, perempuan harus
menunggu dipilih balik. Apa lagi perempuan seperti aku,” aku bisa merasakan
suaraku mulai bergetar. “Dan kali ketiga, adalah sekarang.”
“Aku enggak pernah berharap kamu jadi orang lain,” jawabmu
pelan.
“Rasanya, bagaimana pun aku terlihat dari luar, aku orang
yang sama di dalam. Dan kamu, udah tahu. Yang membuat kamu ragu, adalah
penampilanku, kan?”
“Aku enggak pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Tapi aku
bersyukur kamu dilahirkan sebagai perempuan. Sebagai perempuan, kamu
mengagumkan, Ra. Kamu ada di posisi sekarang, karena kamu perempuan. Kamu
mandiri. Dan kamu enggak membiarkan satu orang pun mengatur apa yang bisa,
boleh, atau harus kamu lakukan. Tapi kamu enggak menyadari itu. Kamu bahkan
enggak sadar betapa kamu sudah menjadi alasan orang lain juga untuk bangun
pagi. Kan?”
Aku memicingkan mata. Menggelengkan kepala. Dari mana
datangnya rentetan kalimat itu? Betapa tidak relevan. Untuk apa mengungkit itu.
Seakan-akan semua itu bisa mengubah keadaan.
“Lalu? Lalu apa?” aku menuntut jwaban yang lebih relevan.
“Iya, kamu selalu mengeluhkan apa yang kamu enggak punya,
apa yang kamu enggak bisa dapat. Apa yang kamu enggak bisa ubah.”
“Maksud kamu, aku kurang bersyukur?”
“Semacam itu.”
“Semacam itu.”
“Maksud kamu, aku harus bersyukur, bisa menyimpan perasaan
bertahun-tahun tanpa bisa melakukan apa-apa? Aku harus bersyukur karena setiap
malam aku merasa kesepian dan enggak ada satu barangpun yang bisa aku beli
untuk menghilangkan rasa itu? Aku harus bersyukur melihat kamu sama Radit,
sementara..”
“Sementara aku ngasih kamu harapan palsu. Makanya, aku
jahat, kan?” katamu memotong kata-kataku.
“Dan kamu… kamu bersyukur?” kataku lagi.
“Radit penting buat aku. Juga kamu. Tapi, sama Radit, aku
enggak harus membelah lautan, memindahkan gunung, pergi ke Mars, atau mencari
obat anti kanker. Kita tinggal di sini, Ra. Bukan di luar sana. Tapi pun di
luar sana kamu pikir gampang? Mereka juga tetap dipinggirkan. Jadi penghuni
kelas dua. Kita? Kamu mau jadi penghuni kelas dua di negara dunia ke-tiga? Kita
harus menerima kalau kita enggak bisa mengubah dunia cuma gara-gara perasaan.”
Kadang kita bisa tiba-tiba merasa tidak mengenal seseorang
yang kita pikir kita kenal, hanya karena beberapa ucapannya. Dan betapa aku,
selama ini, mengira kamu adalah seseorang yang berbeda, yang bukan ini. Bukan
yang sedang di depanku ini memberikan kuliah soal betapa kaum minoritas
dipinggirkan. Aku rasa kalau kalimat selanjutnya yang keluar dari mulutmu
adalah soal agama, tidak ada lagi alasan bagiku untuk duduk diam dan
mendengarkan.
“Karena perasaan kadang salah? Seperti katamu di email?”
kataku lirih. Sementara kau terlihat begitu bersemangat setelah semua
pendapatmu kau keluarkan.
“Iya.” jawabmu singkat.
“Kamu bener, sih. Aku enggak bisa mengubah apa yang aku
enggak bisa ubah. Aku enggak bisa mengubah soal aku dilahirkan sebagai seorang
perempuan. Dan aku juga enggak bisa mengubah perasaan yang aku punya buat kamu.
Dan aku mulai yakin aku enggak bisa mengubah apa yang kamu pikir benar.”
Sorot matamu berubah. Seolah-olah kau baru menyadari bahwa
hasil akhir dari sebuah pertanyaan adalah ini. Adalah sebuah simpulan yang
enggak bisa kita ingkari lagi. Padahal aku yakin kamu tahu, apa maksud dan arah
pertanyanmu tadi. Tapi, kamu mungkin enggak sadar, sebagaimana aku sadari,
bahwa ini adalah akhirnya.
“Nih, akhirnya kamu menggali jalan buat keluar. Kamu
berhasil.” Kataku sambil menatap lekat kedua mata cokelatmu. Dan benar, kamu
tembus pandang. Aku bisa melihat, kamu berusaha menahan air mata. Aku bisa
melihat kamu, terkejut. Aku bisa melihat kamu tidak rela. Tapi, aku bisa
melihat, kamu tenang. Dan kamu hanya bisa terdiam.
“Ya ampun, dari tadi aku telepon enggak diangkat. Kalian
lagi ngobrol serius banget yah?” entah dari mana datangnya, tapi tiba-tiba
Radit terduduk di sebelahmu. Tanpa ragu, dia memeluk dan mencium kepalamu. Lalu
dia tersenyum ke arahku. Aku rasa butuh beberapa detik untuk sadar kalau aku
harus membalas senyumannya, walaupun aku tidak mau.
“Eh, dari mana, Dit?” kataku. Basa-basi yang tak perlu.
“Itu, abis dari beer
garden situ, sama anak-anak yang lain. Aku udah minta Erika nyusul, katanya
mau, eh, lama banget ditungguin. Ditelepon enggak diangkat. Kalau tau dia sama
kamu, aku telepon kamu dari tadi, Dar. Apalagi tadi ada Sakti, dia pasti seneng
banget kalau bisa ketemu kamu,” jawab Radit dengan santai. “Tapi udah pada
balik, sih, terus aku laper, ke sini deh. Eh, ada si cantik. Dan sahabatnya
yang sama cantiknya bagaikan model Victoria Secret,” canda Radit sambil mencium
pipimu.
Sebenarnya enggak ada laki-laki lain yang lebih aku benci dari
Radit. Tapi kalau aku menepikan perasaanku buatmu, sialnya dia memang laki-laki
yang paling baik yang pernah aku kenal. Tidak pernah sekalipun aku melihat dia
membuat kamu sedih. Kalaupun kesal, itu karena semua jokes yang keluar dari mulutnya kadang sulit dipercaya. Untuk
seorang lulusan S2 universitas luar dan bekerja di perusahaan multi nasional,
dia sangat out of character.
Pernah sekali, aku melihat dia sedang nongkrong sambil merokok
dengan penjual minuman di depan kantor kita. Sambil menunggu kamu. Padahal dia
bisa menunggu di mobil, di lobby, atau di Starbucks di gedung kita. Tapi dia
memilih untuk ngobrol ngalor-ngidul sama tukang parkir dan pedagang kaki lima.
Sambil menenteng jas, menggulung kemeja sampai siku, dan jongkok dengan cueknya
di trotoar.
Pernah juga aku melihat dia kebingungan memilih bunga, dan
aku berharap dia memilih bunga yang salah. Tapi dengan pandainya, ia
menceritakan soal kamu pada si penjaga toko, sampai akhirnya si ahli bunga bisa
menebak bunga kesukaanmu. Akhirnya ia datang dengan dua puluh dua tangkai tulip
oranye, yang memang bunga yang kamu suka. Soal 22 tangkai, dengan candanya dia
bilang karena selamanya kamu berusia 22 bagi Radit. Usia di mana kalian
berpisah karena dia harus sekolah di luar. Usia di mana aku pertama kali
mengenalmu. Usia di mana aku pertama kali menaruh perasaan kepadamu. Usia di
mana aku mulai menaruh harapan pada sesuatu yang jelas-jelas jauh dari
kenyataan di hadapanku.
“Dar, jangan ngeliatin aku gitu, dong. Nanti Erika cemburu,
nih,” kata Radit memecah lamunanku. Sambil tertawa ia pun lalu sibuk memilih
menu, sambil sebelah tangannya tak pernah melepaskanmu. Seakan dia tahu,
sedikit saja ia melepaskanmu, kau akan pergi. Seakan dia tahu, sedikit saja ia
melupakanmu, aku siap maju. Sementara kamu, terlihat tenang, seperti berada di
tempat yang seharusnya.
Aku pun merogoh hand phone
dari dalam tas. Lalu mengetik sebuah pesan untukmu, kukirim via email. Membalas
email-mu malam lalu yang belum kubalas sebelumnya. Terkirim. Lalu aku pun
membereskan semua bawaanku.
“Aku duluan, yah, udah malem,” kataku.
“Enggak mau bareng aja? Aku anter!” jawab Radit.
“Duh, kan kamu pernah bilang jangan menghilangkan rejeki
orang Dit. Kasihan abang taksi kalau kamu nganterin aku,” aku mencoba
berkelakar khas Radit.
“Wah, asik Dar! Salam buat abang taksi, bilangin, yang giat
kerjanya buat anak istri di rumah,” kata Radit sambil tertawa.
“Bye,” katamu
pelan.
Sambil berlalu, aku tahu. Ini akan jadi malam terakhir kita
menghabiskan waktu bersama. Aku yakin, setelah malam ini semuanya akan berubah.
Kita enggak bisa lagi menjadi kita, karena ternyata memang tidak pernah ada
kita. Dan aku enggak akan menangis. Karena, aktivitas itu sudah menjadi ritual
harian yang mulai membosankan. Dan karena, aku tahu, perasaanku berbalas. Aku,
tidak gila. Kalaupun aku gila, aku tidak sendirian.
Aku melambai memanggil taksi. Dia pun menepi. Kubuka
pintunya, sambil duduk aku mengatakan alamat tujuan. Aku menyandarkan punggung,
kepala, hingga semua beban yang aku tanggung dan tahan selama ini di kursi
belakang taksi.
“Sambil dengerin radio, ya, Mbak,” kata sang supir taksi.
Aku diam tak menjawab.
Sayup-sayup aku mendengar melodi yang kukenal. Semakin lama
aku semakin yakin, siapa penyanyi dan apa lagunya. Dan kurasa, aku memang
dikutuk. Lagu yang awalnya aku suka sebelum tahu liriknya, menjadi lagu yang
paling mengerikan untuk didengar, dan akhirnya jadi lagu yang pas sekali
menjadi soundtrack scene hidupku malam ini. Sekalian saja habis ini putar lagu Little
Mix yang Erika email malam lalu, lengkap sudah. Pikirku. Dan aku sudah yakin
tidak akan menangis. Sial!
Cancel Re: Untuk Dibaca dan Dihapus... Send
Cc/Bcc:
Subject: Re: Untuk Dibaca dan Dihapus Segera
Dear Erika,
Bukan perasaan yang salah.
Tapi, kamu takut.
Dan aku, terlalu cepat menyerah.
Sent from my iPhone

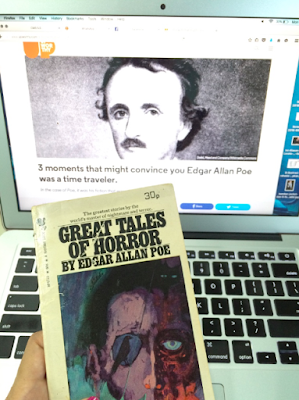

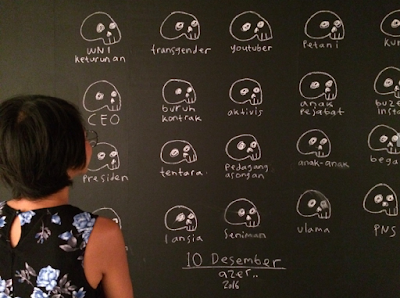
yaaah putus :(
ReplyDelete