Women’s March Jakarta 2017: Buat Saya, Feminis itu Ingin Gender Equality Bukan Benci Laki-Laki
 |
| Met Trump at the Women's March Jakarta! :P |
“Acil, daripada capek-capek belajar, mendingan kamu dandan aja deh. Biar cantik nanti abis SMA nunggu dilamar,” kata teman sekelas saya, cowok, kelas 1 SMA.
Dia ngomong gitu sambil bercanda. Waktu itu saya stress karena mau ulangan Fisika. Dan
saya, seringkali dapat nilai jelek di Fisika. Juga Matematika dan Kimia. In short, saya jauh dari kata pintar.
Karena enggak jago eksakta. Dulu sih gitu yah, kalau pintarnya Bahasa atau Geografi enggak lekat sama kata 'pintar.' Karena peduli sama saya, teman cowok saya itu
ngasih masukan. Yang kemudian diiyakan oleh teman cewek lainnya. Fakta di mana
saya masih mengingat kejadian ini sekarang, 14 tahun kemudian, artinya it matter for me.
Kenapa perempuan
harus seperti itu?
Saya tidak pernah mendengar kata feminis ketika itu. Tapi ada beberapa kejadian yang selalu mengganggu, yang saya enggak tahu apa itu, dan karena enggak tahu itu apa, kadang sulit mengomunikasikannya dengan teman-teman di sekeliling.
Seperti ketika mendengar teman-teman perempuan ribut
ngomongin kalau mereka ngegebet kakak kelas karena motor atau mobilnya paling
bagus. Saya malah pengen punya motor atau mobil bagus biar para kakak kelas
rame-rame ngegebet saya. Tentunya ini enggak kejadian. Baik punya motor atau
mobilnya juga para lelaki rame-rame ngegebet saya.
Seperti ketika saya menenangkan teman perempuan saya setelah
dilabrak karena jalan sama senior laki-laki yang udah punya pacar. Sementara
yang cowoknya tetap disayang, “namanya
juga laki-laki,” kata pacarnya. Lah! Kan yang salah dua-duanya. Emangnya
masnya diculik ke bioskop terus dibalikin lagi ke rumahnya? Kenapa cuma teman
saya yang dipanggil perek di depan
umum?
Seperti ketika mantan pacar saya ketika itu marah karena
saya berdiri di sisi menantang lalu lintas ketika menyeberang jalan. Yang
seharusnya saya sembunyi di samping badan dia dan nunggu digandeng. Dan ketika
dia insist bayar semua yang saya
makan padahal saya tahu dia enggak punya uang. Teman-teman perempuan saya sih
pada komentar, “awww…so gentle.”
Sementara saya merasa there’s something
odd about this.
Ada stigma yang melekat erat pada perempuan dan laki-laki.
Yang keduanya kadang berbeda sekali. Yang membuat saya uneasy, bertanya-tanya,
dan merasa tidak puas. Kenapa perempuan harus seperti itu?
Saya bukan feminis
Pertama kali mendengar kata feminis adalah di kampus. Mahasiswa Komunikasi sih enggak secara spesifik belajar ini di kelas. Tapi kadang kita lebih banyak belajar di luar ruang kelas, kan? Sayup-sayup makin banyak perempuan yang ngomongin kata ini, membaca bukunya, bahkan juga yang dengan lantang bilang dia feminis.
Masalahnya, ketika itu entah kenapa yang lekat di kepala
saya image seorang feminis itu enggak
peduli penampilan, ngomongnya kasar, enggak mengikuti fashion, dan benci laki-laki.
Mungkin sebagian karena saya wawancara seorang sosiolog feminis yang bilang, “perempuan enggak
butuh penis untuk orgasme.” Dia ngomong banyak hal, ini yang paling nempel
di kepala. Saya lupa nama beliau, tapi image
beliau sangat stereotype seorang
feminis. Dan ketika itu saya merasa kalau saya bukan feminis. Walaupun beberapa
teman perempuan saya merasa keren dengan label itu. Saya tidak.
Saya peduli dengan gender
equality. Seumur hidup, itu yang berusaha saya buktikan pada orangtua dan
lingkungan. Kalau sebagai perempuan, saya setara. Saya sama mandirinya dan saya
sama-sama berhak untuk mengejar impian saya. Impian yang hanya ditentukan oleh
saya seorang, tanpa dipengaruhi oleh gender
expectations.
Tapi kalau feminis adalah benci laki-laki, saya bukan
feminis. I care about how I look,
saya suka fashion. Waktu kuliah saya
dan beberapa teman dapat julukan ‘geng kalung.’ Seakan-akan peduli pada
penampilan membuat kami enggak peduli dengan isi otak. Padahal, teman-teman
geng kalung saya ini, adalah para perempuan pintar dan mandiri. Dan sebagai
anak perempuan dari keluarga Jawa-Sunda dan tinggal di kota kecil, saya enggak
terbiasa ngomong kasar. So, I guess I’m
not a feminist? Begitu pikir saya ketika itu.
Don’t label it, just
do it
Bekerja di divisi lifestyle media, yang mana mungkin hampir 80% isinya perempuan, saya belajar makna baru tentang feminisme. Di tempat saya bekerja ini kata feminisme jarang disebutkan, tapi jamak dibuktikan. Saya berkenalan dengan banyak perempuan pemegang jabatan tinggi. Saya melihat para perempuan yang jadi kepala keluarga. Saya berkenalan dengan banyak perempuan mandiri dan punya goals yang menginspirasi.
Saya bertukar pikiran dengan banyak perempuan yang satu
pemikiran dengan saya, yang menjawab keresahan saya sejak remaja, dan akhirnya
memberikan jawaban konkrit dengan contoh nyata kalau; perempuan enggak harus
seperti itu! And they speak in an elegant
way, smells good, loves men, and oh so in fashion. It gives me hope. Sejak
itu saya enggak fokus pada labelnya, tapi terus praktek dalam melakukannya dan
menuliskannya karena saya seorang penulis.
Saya bukan perempuan yang akan kesal pada laki-laki yang
enggak mau ngasih saya duduk di bus. Saya tahu mereka juga capek. Tapi saya
akan marah membabi buta kalau saya dicolek. Baca pengalaman saya soal ini di sini. Saya juga enggak mau ikut-ikutan extreme
feminism, who march on the street in
their underwear. Sebagai bukti kalau seorang perempuan boleh melakukan
apapun dengan tubuhnya dan bukan urusan orang lain. It’s true, I agree, but I’m not that. And I don’t think that is what it’s
really about.
What it really means
to be a feminist?
“Jaman sekarang masih
musim ngomongin women empowering? Kan perempuan udah boleh jadi apa aja,”
kata rekan kerja, A, laki-laki.
“Kayaknya sekarang
udah enggak ada yah perempuan yang digodain atau dicolek di jalan,” kata
rekan kerja, B, laki-laki.
“Masih ada emang,
istri yang dilarang kerja sama suaminya, hari gini?” kata rekan, C,
laki-laki.
“Enggak ada masalah
lain, masih ngomogin itu?” kata teman, E, perempuan.
“Temen kamu yang
feminis itu, segitu bencinya sama laki ya?” kata rekan kerja kerja lainnya,
D, laki-laki.
Jawaban untuk pertanyaan pertama adalah kapital YA! Masih musim ngomongin women
empowering. Karena kenyataannya tingkat perkawinan anak dan kehamilan
remaja di Indonesia masih tinggi. Dan ini cenderung mengakibatkan putus
sekolah. Sebanyak 91% perempuan yang menikah sebelum usia 18 tidak
menyelesaikan sekolah. Dengan pendidikan yang rendah, mereka cenderung memiliki
keterbatasan dalam partisipasi angkatan kerja, dan memperoleh pendapatan yang
layak (data dari Susenas 2015, BPS 2016).
Masih banyak perempuan yang jadi korban catcalling dan pelecehan seksual di jalan. Bahkan, menurut Komnas Perempuan, terdapat 259.150 jumlah kekerasan terhadap perempuan di tahun 2016. Kekerasan
ini terjadi mulai dari di lingkungan personal, komunitas, sampai lingkungan
kerja. Seringkali tidak ada yang peduli untuk menolong dan banyak dari mereka
malah kembali disalahkan. Victim blaming
is shit. Selama perempuan masih dilihat sebagai ‘objek’ instead of ‘subjek’ hal kayak gini akan
terus terjadi.
Masih ada istri yang dilarang bekerja oleh suami dengan
anggapan perempuan itu harus diam di rumah. Bukannya semua perempuan harus
kerja. Tapi, mau di rumah atau bekerja, sebaiknya jadi pilihan perempuan itu
sendiri atau memang kesepakatan bersama. Bukan sesuatu yang wajib melekat
padanya tanpa ia punya pilihan. Ngerinya lagi, masih ada perempuan yang dilarang
kerja sementara suaminya juga enggak memberikan penghasilan yang cukup untuk survive. This is just madness.
Duh, masalah mah banyak. Yang personal juga enggak habis-habis.
Tapi ini krusial, apa lagi untuk saya yang pekerjaan sehari-harinya menentukan
tulisan seperti apa yang akan dibaca oleh remaja perempuan di Indonesia. Di
mana kami sadar, ngomongin gender
equality ke remaja yang lagi digempur nada pemberitaan yang masik sexist itu susah. Karena yang harus
diedukasi soal ini bukan cuma laki-laki tapi justru perempuannya sendiri. Enggak
mau kan, remaja kita bacanya artikel-artikel dengan judul macam ini tiap hari?
 |
| cih. digombalin? |
 |
| memangnya kalau di pantai harus pake apa? |
 |
| apes? APES? |
 |
| sehingga, jangan ditolak? |
| terus, kalau cowok minder, kita rugi, gitu? |
Forgive me if I’m
wrong, saya juga masih belajar, tapi bagi saya, inti feminisme adalah gender equality. Memberikan kesempatan yang sama untuk semua gender. Memberikan penghargaan dan
memperlakukan semua gender dengan
hormat. Saya paham, laki-laki dan perempuan berbeda, apalagi secara biologis, selamanya
enggak akan sama. Bukan laki-laki dan perempuannya yang harus sama, tapi
kesempatannya.
Enggak! She loves men.
And so do I. I am married to one. Karena sekali lagi, rekan sekalian,
feminis itu ingin gender equality,
bukan benci laki-laki.
And I’m not gonna be
angry anymore, or point at your head while talking, or seems like full of hate.
I’m gonna be me. Because that is what feminism taught me, to be me, to be the
best version of me who have a choice, without having other people tells me what
not and to do. And that’s also what makes me march, slowly, steadily, and
gracefully in fashion last 4th March.
 |
| Turun ke jalan bersama redaksi cewekbanget.id. |
We need to stop playing Privilege or Oppression Olympics because we’ll never get anywhere until we find more effective ways of talking through difference. We should be able to say, “This is my truth,” and have that truth stand without a hundred clamoring voices shouting, giving the impression that multiple truths cannot coexist.” ― Roxane Gay, Bad Feminist: Essays.




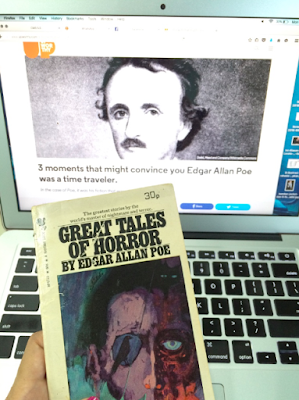

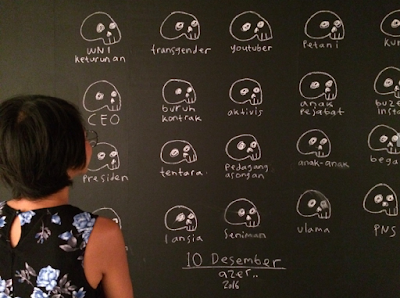
Comments
Post a Comment