Tersesat Mengartikan Senyuman Erika
They said, we could be
whoever we want to be.

Ini akan jadi hari terpanjang dalam hidupku, aku bisa
merasakannya.
Lima belas menit berjalan menuju halte bus. Sepuluh menit
menunggunya. Lima menit di dalamnya. Tiga menit berjalan menuju kantor. Dua
menit menunggu lift yang membawaku ke atas. Lantai satu, enam, sembilan, lalu…
empat belas. Satu menit berdiri di depan pintu masuk. Sebelum akhirnya, aku
mendorong salah satu pintu kaca, masuk, lalu terduduk di depan meja kerja.
Kutatap jam di dinding, pukul 8.45 WIB. Dan aku sudah mereka-ulang perjalanan
pagi ini sejak pukul 02.00 WIB tadi di kepalaku. Seperti kubilang, ini akan
jadi hari terpanjang dalam hidupku, aku sudah bisa merasakannya.
Kusiapkan hati, melirik ke kanan, ke mejamu yang kelewat
rapi itu, yang hanya ada satu vas bunga tanpa bunga dan sebuah frame foto tanpa foto. Kau belum datang.
Dan aku bersyukur. Aku punya waktu sepuluh menit menyimpan semua tulisan yang
sudah kubuat ke server data. Sengaja
sudah kukerjakan di kamar kos. Supaya tak harus ku duduk seharian di meja
menuliskannya. Lalu aku punya waktu lima menit untuk bergegas turun, menyetop
taksi, memintanya segera mengantarku ke tempat meeting. Meeting yang
sudah dijadwalkan sambil makan siang. Ya, makan siang. Dan aku akan berangkat
ke sana dalam lima belas menit lagi. Tiba sekitar tiga jam sebelum meeting dimulai. Semua sudah
kurencanakan sejak kemarin. Kemarin. Hari terberat dalam hidupku.
***
Semua tulisan sudah masuk. Kubereskan semua alat kerjaku.
Memasukkan kembali laptop ke dalam
tas. Rasanya tak lama aku menunduk, merapikan semua isi tas, tapi ketika aku
menengadah, menoleh, kulihat terduduk kau di situ, di kursimu, di sampingku.
Tak ada sapa. Kau hanya terdiam, duduk dan terdiam, memainkan smartphone-mu, sepertinya kau sedang chatting dengan seseorang. Mungkin
obrolan pekerjaan, karena kau sama sekali tak tersenyum, tak ada ekspresi. Hah, tak ada ekspresi, justru ini adalah
ekspresimu akhir-akhir ini. Sejak…
“Mau ke mana?” tanyamu tiba-tiba, tanpa menoleh.
“Eh?”
“Ada meeting?”
tanyamu lagi, masih sibuk menatap layar smartphone.
“Iya. Itu, meeting
lanjutan yang waktu itu,” jawabku sedikit terbata.
“Okay, good luck,”
katamu, sambil berlalu, entah ke mana, ke toilet?
Aku terlambat. Interaksi yang aku takutkan terjadi, terjadi.
Yang aku bayangkan di kepala semalaman tadi, yang coba aku hindari. Aku
terlambat. Dan seperti imajinasiku, interaksi ini, sama sekali tidak membuat
hubungan kita lebih baik. Andai aku datang lebih pagi dan pergi lebih cepat,
kita tidak perlu mengalami ini. Percakapan basa-basi yang akhir-akhir ini
satu-satunya interaksi yang kita punya, sejak…
“Masih belum berangkat?” tanyamu membuyarkan lamunan.
“Ah, iya, mau. Kamu dari mana?”
“Hemm,” hanya suara itu yang keluar dari mulutmu.
Aku menarik napas, berdiri, menyelempangkan tas di bahu kanan,
bersiap melangkah menuju lift. Aku harus siap menerima semua jawaban pendekmu,
matamu yang enggan melihat bayanganku, dan senyumu yang tidak akan lagi
mengembang untukku. Aku, harus, siap.
“Enggak usah pakai taksi, diantar Pak Rahman aja. Udah aku
panggilin barusan. Udah di lobby,”
ujarmu di balik punggungku.
Jantungku berdegup. Begitu kencang, aku bisa mendengarnya.
Tiba-tiba aku seperti bisa merasakan darah mengalir dari ujung kepala ke dahi,
ke kelopak mata, ke pipi, hangat. Sial.
Ini bukan darah yang mengalir di pipi. Aku mengusapnya dengan panik, tanpa
sadar kakiku melangkah begitu lebar, dengan tempo yang cepat, seperti berlari,
seperti hilang kendali, dan aku tak menengok ke belakang, tak sempat ucapkan
terima kasih. Sibuk mengeringkan wajah tanpa sapu tangan, tanpa tissue.
***
“Ke tempat meeting
Senin lalu, ya, Pak,” kataku pada Pak Rahman begitu duduk di kursi belakang.
Masih sibuk membereskan wajah yang berantakan. Untungnya hari ini aku tidak
memakai mascara atau eyeliner. Bahkan untuk memulas wajah,
aku tak ada tenaga.
“Kita nunggu siapa lagi, Pak? Tanyaku ketika sadar mobil
tidak bergerak satu meterpun.
“Itu dia, datang,” kata Pak Rahman sambil menunjuk ke pintu lobby. Kuarahkan pandang ke mana
telunjuknya mengarah. Dan jantungku tiba-tiba berhenti.
***
“Bukannya nungguin,” katamu sambil membuka pintu, memberikan
isyarat untukku bergeser, lalu duduk. Dan tampaknya aku tidak cukup jauh
bergeser, karena pundakmu yang berbalut jaket kulit ada tepat di depanku.
Karena wangi parfummu yang manis dan menggigit itu bisa kucium dengan jelas.
Karena ketika kau menoleh, aku seperti sedang melihatmu melalui kaca pembesar,
tepat di depan mata. Mata yang bulat dan cokelat itu, akhirnya menatapku lagi.
“Emm, boleh geser, dikit lagi?” katamu dingin. Aku bergeser
dalam diam. Memalingkan tubuh ke kiri, berusaha mengatur napas. Menatap ke luar
jendela mobil, menatap entah apa. Begitu banyak pertanyaan muncul di kepala.
Kau mau ke mana, kenapa naik mobil juga, kenapa, ah! Jangan-jangan maksudnya kau mengajak pergi bareng dan aku salah
paham?
“Ah, kamu ada meeting
juga, yah? Mau ke tempat kamu dulu?” aku berusaha mencairkan suasana.
“Enggak,” jawabmu santai.
“Eh?”
“Meeting-nya
sambil makan siang, kan? Kamu mau nunggu di sana tiga jam sendirian? Pasti
bosan,” katamu. Aku hanya bisa menatapmu, melihat rambut pendek yang kau tutupi
beanie, beanie kesukaanmu itu. Aku
tak tahu bagaimana kau bisa tahu. Aku tak tahu harus menjawab apa. Aku tak tahu
harus berpikir apa. Aku tak tahu harus bagaimana. Ini semua seperti, mimpi.
Tiba-tiba kau menoleh ke arahku,
“Iya, kan?” lanjutmu. Sambil tersenyum ke arahku. Membuatku
semakin kelu. Aku hanya bisa mengangguk, tak sanggup rasanya menatap kedua bola
mata cokelatmu. Dan ketika kuarahkan mataku padamu, sekali lagi, hanya bagian
kepalamu yang kutemui. Tak mengapa, aku suka, aku suka melihatmu yang sedang memandang
ke kejauhan.
Dan kita melaju, perlahan, tanpa obrolan. Walau sesekali kau
bergurau dengan Pak Rahman. Aku merasa cukup, ikut mendengarkan. Gurauanmu,
tawamu, suaramu.
***
“Nanti pulangnya pakai taksi, Pak, enggak usah dijemput,”
katamu tiba-tiba. Lalu membuka pintu dan turun dari mobil. Ternyata kita sudah
sampai. Aku buru-buru turun, sambil memeriksa kembali kalau-kalau ada yang
tertinggal di kursi mobil. Setelah yakin, kututp pintunya. Mobil berlalu, dan
di baliknya, kuliat sosokmu. Berdiri tepat di depanku, menatapku. Lalu
berpaling, melaju. Tanpa harus mengatakan sesuatu, aku mengikutimu.
Kau memilih meja tepat di samping jendela. Tentu saja. Kau
dan jendela. Aku tersenyum sendiri bangga pada diri sendiri karena di balik
semua sikap dinginmu akhir-akhir ini, aku masih mengenalimu. Kau masih yang
dulu, di dalam sana, jauh di dalam sana, kau masih orang yang sama.
Kau mengerenyitkan dahi sambil melihat ke arahku, heran aku
tersenyum sendiri. Tapi lalu sibuk mengeluarkan laptop dari tas, membukanya, lalu sibuk mengetik. Aku duduk di
depanmu. Dengan gugup memegang menu, pelayan berdiri tepat di samping kiriku,
menunggu.
“Mau pesan apa?” tanyaku.
“Apa aja.”
“Ih, apa?” tanyaku lagi.
“Yang kemarin kamu pesan, apa? Di Bandara?” tanyamu sambil
tetap sibuk menggerakkan kedua tangan di atas keyboard.
“Chai tea latte?”
“Oke. Hot,”
jawabmu tanpa mengalihkan pandangan dari layar laptop.
“Hot chai tea
latte, grande. Sama hot peppermint tea, grande. Emm, cappuccino browniesnya satu, minta diangetin lagi,
yah, Mbak. Itu aja,” kataku pada pelayan. Setelah mengulang semua pesanan, dia
pergi.
“Kok enggak sama?” tanyamu.
“Aku mau kita beda.”
“Oh. Aku mau kita sama,” jawabmu. Berhenti mengetik, tangan
kiri menopang dagu, tangan kanan memainkan track
pad. Sama sekali tak mau menatapku. Entah apa yang kamu maksud dengan itu, maunya sama? Apa itu? Lalu suara keyboard-mu memecah lamunanku.
Kau kembali larut dalam pikiranmu dan tatapanmu terkunci
pada kata-kata yang kau rangkai. Pemandangan yang indah bagiku. Sesekali kau
benahi letak beanie-mu, menariknya ke
depan, ke belakang, selalu begitu ketika kau memikirkan sesuatu.
Diam-diam aku berharap waktu berhenti di sini. Sehingga tiga
jam dari sekarang tidak ada yang datang, tidak ada pertemuan membicarakan
pekerjaan, tidak ada keharusan kembali ke kantor, tidak ada rutinitas, tidak
ada apapun. Hanya ada aku yang sibuk menatapmu menatap layar laptop. Dan perjalanan terpanjang dalam
hidupku pagi tadi, terbayarkan.
“Kalau kamu ngeliatin terus, aku enggak konsen nih,
ngetiknya,” katamu tiba-tiba. Membuatku kaget dan tersipu. Segeralah kutarik laptop dari tasku, membukannya, lalu
membenamkan sebagian besar wajahku di balik layarnya, bersembunyi darimu,
sambil sibuk menyalakan Wi-Fi.
“Eh, kok enggak nyala?” kataku dengan volume suara yang agak terlalu kencang. Tak lama salah satu pelayan
menghampiri, memberi tahu kalau Wi-Fi sedang down, dan akan segera diperbaiki. Setelah meminta maaf dengan sopan
dia pun pergi. Mendengarnya, kau hanya tersenyum lalu menutup laptop. Lalu menutup paksa laptop-ku dengan satu gerakan jari
telunjuk. Kemudian menyeruput hot
chai tea latte, kesukaanku, yang kau pesan. Sambil menatap jauh ke luar
jendela.
“Kompleks, ya,” katamu.
“Apa?”
“Ini, rasanya.”
“Oh. Iya. Semua yang aku suka, rasanya kompleks.”
“Ya.”
“Ya?” tanyaku, penasaran apakah dia benar-benar merasa
mengenalku, seleraku.
“Iya. Aku juga, kompleks.”
Mendengarnya mataku membelalak. Kedua telapak tanganku
bergetar. Kutarik keduanya ke bawah meja, berusaha menyembunyikannya, sambil
menenangkannya. Tapi bukan tangaku saja, jantungku. Bibirku. Napasku tersengal.
Aku mulai merapikan rambutku yang sama sekali tak perlu kulakukan. Aku berusaha
membalas jawabanmu dengan cepat, dengan lucu, dengan… aku kelu.
***
“Waktu itu…. Maaf, yah,” katamu pelan. “Lalu, kemarin,
juga,” lanjutmu semakin pelan. Ketika kau mengatakan sesuatu dengan pelan,
suaramu terdengar sangat lembut. Lebih lembut dari biasanya. Membuatku semakin,
kelu.
“Kepalaku penuh, seperti mau meledak. Jadi aku bingung harus
gimana. Jadi aku pergi. Kamu, pasti kaget, ya?” tanyamu, lembut. Dan matamu,
ah, matamu yang bulat dan cokelat, mengarah tepat ke mataku. Sementara aku
hanya bisa mengangguk.
“Dan kemarin. Kemarin itu, hari terberat buatku.” Kau pun
menutup wajah dengan kedua telapak tanganmu setelah berkata begitu. Mengatakan
apa yang ada di kepalaku. Perasaanku campur aduk. Tak menyangka kau merasakan
apa yang aku rasakan juga. Aku senang. Tapi sekaligus sedih, melihatmu, wajahmu
memerah, aku bisa melihatnya di sela-sela jarimu yang panjang. Semakin jelas
memerah, dibandingkan dengan cat kukumu yang hitam legam. “Maaf, yah,” katamu
setengah bergumam.
Tak kusangka, hanya satu kalimat ini bisa membuatku lupa.
Lupa pada betapa kagetnya ketika kau menolak ditugaskan pergi ke luar kota
bersamaku. Lupa pada perasaan kecewa ketika kau memberikan begitu banyak argumen
mengapa aku tak pantas mengerjakan tugas itu denganmu. Lupa pada rasa marah
ketika kau mengatakan terpaksa harus tetap melakukan perintah, mengerjakannya
bersamaku. Lupa pada sakit hati dengan sikap dinginmu selama hampir dua puluh
empat jam kita bersama. Lupa pada rasa malu, ketika kau tak membalas ciumanku.
***
“Tapi aku… aku mau minta kamu nunggu,” katamu dengan serius.
Aku tak mengerti apa maksudmu. Dan kau bisa melihatnya. Selama ini, hanya
dengan melihatku sekilas saja, kau sudah bisa tahu apa yang ada di pikiranku.
Dasar kau pembaca pikiran, orang!
“Okay, gimana yah, cara menjelaskannya,” gumammu pada diri
sendiri, sambil menunduk dan menggosok kedua mata dengan jari tengah, telunjuk,
dan jempol kananmu. Lalu menengadah dan membuka mata, menatapku, menarik napas,
lalu membuangnya.
“Aku mau kamu nunggu sampai aku tahu siapa aku, apa yang aku
mau, dan gimana perasaanku soal ini, soal kamu,” jelasmu. Aku hanya bisa
terdiam sambil menggigit bibirku. Menahan kata yang ingin aku katakan, sejak
pertama mengenalmu. Aku hanya bisa terdiam sambil meremas kedua telapak tangan.
Menahan apa yang ingin aku lakukan, sejak pertama melihatmu. Lalu aku pun
mengangguk pelan.
Lengkingan suara laki-laki mengejar nada tinggi memecah
ketegangan. Aku terperanjat saking kagetnya. Kau tersenyum geli. Suara
laki-laki itu lagi, yang melengking, seperti Chris Martin tapi bukan, nada
dering smartphone-mu.
“Sial. Merusak momen,” pikirku.
Sambil masih tersenyum geli, kau angkat smartphone-mu, yang hitam itu. Menerima telepon, entah dari siapa.
Kau hanya menjawab sedang ada di mana. Dan mengatakan akan kembali ke kantor,
secepatnya. Lalu kau simpan kembali dia di meja. Lalu kau menatapku, kembali
tersenyum, lalu tertawa, terpingkal. Membuatku malu. Andai ada lubang, aku
sudah memasukkan kepalaku ke sana, supaya tak terlihat betapa merahnya wajahku,
panas.
“Matt Healey,” ujarmu.
“Siapa?”
“Vokalis 1975. Ini, ringtone.”
“Oh.”
“Aku pernah baca di salah satu wawancara, dia bilang; dapat
perhatian, disukai itu selalu menyenangkan. Mau dari cowok atau cewek. Selalu
menyenangkan dianggap menarik sama seseorang, jenis kelamin enggak jadi
masalah,” jelasmu sambil menyeruput lagi minuman yang ada di depanmu.
“Siapa?” tanyaku.
“Matt Healey!”
“Matt atau…?” tanyaku setengah menggoda, tapi serius.
Jantungku berdegup kencang.
“Matt. Dan aku. Sepertinya,” jawabmu sambil tersenyum.
Senyum yang dulu. Senyum yang selalu kurindu. Senyum yang kau tularkan
kepadaku. Senyum yang meyakinkanku untuk menunggu.
***
“Ah, kalian ada di sini. Dara, Erika, lagi apa?” pertanyaan dari
seorang kenalan yang tiba-tiba menghampiri dan duduk di meja kami, menghapus
senyuman di wajahnya, berganti dengan kaget dan sedikit horor. Tak pernah
kulihat ia segugup itu. Dan aku pun tahu, akan panjang waktu yang akan
kutunggu. Aku menarik napas panjang, memaksakan bibir untuk tersenyum dan
terlihat tetap tenang. Aku, harus, tenang.
Dan waktu menunjukkan pukul 10.45 WIB. Seperti kubilang,
hari ini akan akan jadi hari terpanjang dalam hidupku, aku bisa merasakannya.
“Mau meeting, nih,
kamu?” jawabku.
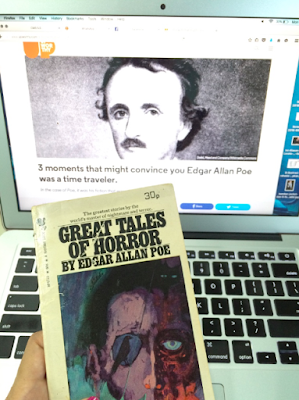

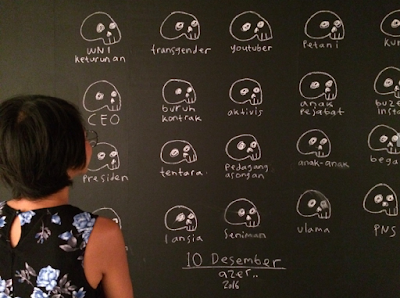
Comments
Post a Comment