Mungkin, Sedih Itu Bukan Fase, Tapi Jati Diri
"I've always spent more time with a smile on my face than not, but the thing is, I don't write about it," Robert Smith.
Melamun atau menyanyi di depan jendela kaca menatap nanar ke
luar. Ibu saya bilang, sejak kecil itu hobi saya. Entah meniru siapa, karena
anggota keluarga lain enggak begitu. Mungkin meniru Candy dari anime Candy-Candy. Tapi kebiasaan ini berlanjut.
Di SMP saya suka menangis di Jumat siang kalau gerimis.
Enggak tahu kenapa jumat siang ketika itu sering gerimis. Ketika teman bertanya
kenapa saya nangis, saya enggak punya alasan khusus. Saya merasa sedih aja, kayaknya
banyak hal menyedihkan yang terjadi di dunia, hallah. Mungkin saya cuma sedih
karena menjelang weekend, enggak
ketemu sama teman atau gebetan.
Kelas dua SMA saya mulai tertarik dengan warna hitam. Tas,
jaket, scarf, aksesori, sampai cat kuku saya warnanya hitam. Ini perubahan
drastis, karena awalnya saya suka warna merah. Kelas dua SMA adalah masa kritis
pertama saya. Itu adalah momen di mana saya tahu kalau hidup itu susah. People lies, marriage failed, betrayal comes
from people that we trust, losing a good father figure, learn how fragile a
woman can be, people go, and broken heart sucks, all at once. Ditambah teenage
angst, hasilnya adalah remaja tanggung yang menutup telinga dan berbuat
sesuka-suka, rebellious and annoying.
But deep inside, I’m just sad.
Di kampus bertemu dengan fellow
aliens yang sama-sama suka berbagi betapa sendunya hidup ini. Yailah.
Malesin memang. Tapi kenyataannya begitu. Dan dengan beberpa orang ini saya
merasa attached, merasa datang dari
planet yang sama. Kami yang kalau nonton konser sukanya duduk di belakang
sendirian sementara yang lain joget, dan memandang asing bagaikan mereka itu
ngomong pakai bahasa burung.
Fase galau dalam
hidup
“Udah enggak jaman
kali, galau,” kata salah satu teman beberapa waktu lalu, menanggapi salah
satu postingan blog saya yang
sebelumnya.
Sebagai penghindar konfrontasi langsung, akut, saya
menanggapinya dengan enteng. Andalan saya adalah, tertawa. Karena mungkin
memang iya, udah enggak jamannya, bagi sebagian orang. Yang kemudian enggak
saya deklarasikan di kesempatan itu adalah, bagi saya, being sad is not a phase, it’s just simply who I am. And it doesn’t
make me a bad person. It just made me the person I am today.
Saya menyadari ini pagi tadi, di kamar mandi, ketika
mendengarkan Radiohead. Tiap pagi memang saya memutar musik sesuai mood sambil melamun. Kadang melamunkan
hidup, kadang menyusun rencana kerja hari itu, kadang tema blog, atau impian
yang mau saya capai, kadang kesalahan yang pernah saya perbuat, kadang baca
artikel. Bermenung sih bukan melamun, karena otak saya terus berputar dari satu
ide ke yang lainnya. Enggak kosong.
Harus banget selalu
hepi
Kita hidup di kultur yang terlalu menjunjung tinggi emosi
‘positif.’ Ingat sadness di film Inside Out? Betapa dia jadi minoritas di
sana, walau akhirnya dijelaskan kalau peran dia sama pentingnya dengan joy dalam hidup seseorang. Seperti yang
dituliskan Atalanta Beaumont, seorang psychotherapist,
sadness enggak selalu bisa diterima
masyarakat atau sebuah kultur karena orang merasa enggak nyaman menyaksikan
kesedihan orang lain. Malah ketidaknyamanan ini kadang memicu amarah. This is how our society shapes us.
Sadness yang saya
maksud di sini bukan depresi. Being sad
is not necessarily depressed. Depresi adalah keadaan mental yang merupakan
gabungan dari beberapa hal yang bukan hanya merasa sedih.
How to treat sadness?
Ada satu penjelasan soal perasaan sedih yang menyentuh
sekali yang saya baca di Psychology Today:
“Sadness is a normal response to a wound that's ultimately destined to
heal.”
Kita punya luka, kan? Asalnya bisa dari mana saja. Dari
kegagalan, kekecewaan, atau diakibatkan orang lain. Dan reaksi normal kita
terhadap luka yang belum sembuh ini adalah perasaan sedih. Yang mana, luka ini
akan sembuh dan rasa sedih itu akan berkurang hingga perlahan hilang.
Karena perasa dan pemikir, luka-luka mini (dan maksi) ini
banyak bersemayam pada saya, dan saya rasa pada banyak orang, pada kamu juga.
Bedanya, setiap orang menghadapi rasa sedih dengan berbagai cara yang berbeda.
Sayangnya, kadang, karena bentukan kultur tadi, kita jadi enggak tahu bagaimana
caranya mengatasi perasaan sedih ini. Kita denial,
memendamnya, berpura-pura, mengubahnya jadi amarah, atau lebih buruk lagi terus
mengurungnya hingga menimbulkan depresi.
Padahal, setuju dengan pendapat Alex Lickerman, M.D.seorang dokter
internist (dokter saya banget), yang
bisa kita lakukan terhadap sadness is
juts to tolerate it. Until it heals,
even though we don’t know when. Dan di sini lah menurut aku perbedaan
mendasar being a sad person and a
depressed person. A sad person know that somewhere along the way, we will be
happy, we hold on to a hope, how little it may be, we have it. But a depressed
person sees no light in the end of the tunnel.
Keunggulan sad person
Joe Forgas, seorang social
psychologist, menemukan tujuh keunggulan sad person. Dua di antaranya bisa saya amini, nih. Pertama, kata
ahli yang secara spesifik meneliti tentang sadness
ini, a sad person lebih skeptis dan
enggak mudah terpengaruh informasi, mitos, dan bisa melihat seseorang yang
enggak tulus.
Kedua, sad person
enggak mudah menyerah ketika mengerjakan tugas yang sulit karena punya motivasi
yang kuat. Dan enggak menyabotase dirinya sendiri sehingga gagal dalam
melakukan tugasnya. Oke, pasti mikir, ya gimana orangnya, lah. Tapi kan ini
simpulan penelitian ya, jadi kalau ada penelitian lain ya ada simpulan lain.
Walaupun sebagai sad person, saya
merasa kedua hal ini saya banget. Sementara lima kelebihan lainnya baca aja di sini.
Sadness motivates me
Ngomongin soal motivasi, tanpa saya sadari, ini lah yang
mendorong saya melakukan banyak hal. Motivasi kuat untuk make this world a little bit better at least for me, more so for others, dan akhirnya menggerakkan saya
to do a thing or two.
Sederhananya, karena sedih saya ingin berusaha bahagia.
Untuk itu saya benar-benar mempertimbangkan, apa sih yang membuat saya bahagia.
Yang bisa saya upayakan sensiri, yang enggak menggantungkan kebahagiaan di
tangan orang lain.
Dalam hal pekerjaan misalnya, oke saya ditawari pekerjaan
dengan salary lebih besar tapi
lingkup kerjanya sempit. Sementara saya ingin bebas create dan enggak melakukan tugas yang itu-itu saja. To be able to create something from nothing
to something, this makes me happy. Jadi saya akan selalu mengupayakannya.
Dalam keseharian misalnya. Saya sedih melihat pendidikan di Indonesia.
Kesedihan ini menuntun saya untuk ikutan sebuah gerakan. Dan terus berupaya
mencari tahu cara bagaimana saya bisa lebih terlibat. Dan berharap bisa lebih
banyak terlibat namun tentunya sesuai kemampuan saya.
Untuk diri saya sendiri misalnya, saya sedih kalau ditanya
sesuatu terus enggak bisa jawab. It
happens a lot lately. Karena terjun ke area yang enggak saya pelajari di
kampus sebelumnya, karena ‘nyebur ke kolam yang lebih besar,’ dan karena newbie di posisi, ada masanya saya
merasa, I wish I were Google, but I’m
not. I can’t always give you an answer. Dengan sedih, saya berusaha belajar
lagi dan berdoa (sambil berusaha) untuk bisa sekolah lagi. (Minta doanya).
Dan tentunya perasaan ini juga yang menjadi alasan pertama
saya menulis. Dan alasan mengapa saya masih menulis.
The truth is, this
ache leads me places.
Tapi enggak lantas
semua orang harus sedih
Ya enggak, lah. A sad
person juga enggak terus-terusan meratap. Maksudnya sih, you can be a happy person or a sad one, it’s
okay. As long it moves you to where you feel you belong, to the place you want
to be, to the real you. Just because it works for you doesn’t mean that’s how
it works for other. Your truth, my truth, and other people’s truth can coexist.
And it can be hard
sometimes being who we really are. Especially when the society despise you. But
when you feel like giving up, believe those scientist when they said, we are far
more resilient than we think. So hold on.



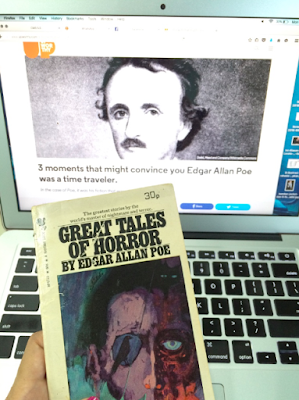

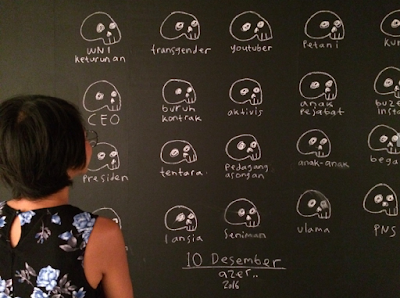
Comments
Post a Comment