Lalu, Kalau Sudah Gagal Harus Ngapain?
“Life is full of screwups.
You're supposed to fail sometimes.
It's a required part of the human existance.”
"Enggak enak tahu Cil jadi orang kayak kamu. Enggak tahu rasanya gagal. Kamu enggak akan bisa bangkit sekalinya kamu gagal nanti."
Gitu. Kata seorang teman. Lebih dari tujuh tahun lalu. Malam ini tiba-tiba ingat. Sering, dong, udah wangi habis mandi dan rebahan di kasur siap tidur eh tiba-tiba teringat kejadian random di masa lampau?
Balik lagi ke omongan teman saya itu. Alkisah waktu itu kami kuliah semester akhir. Saya sedang sibuk menyelesaikan bab sekian skripsi sambil kerja di salah satu media massa cetak di Bandung. Sebenarnya masa kuliah saya standar, mengambil SKS padat yang memang sudah sewajarnya. Tapi saya enggak pernah bolos kuliah atau mengulang apalagi ikut kelas angkatan bawah. Jadi buat dia, saya ini itungannya enggak pernah gagal. Buat dia.
Reaksi saya ketika itu cuma tersenyum. Di satu sisi jadi kepikiran, "emang iya saya enggak pernah gagal? Atau kalau dibandingkan dia, kegagalan yang mungkin pernah saya alami bukan apa-apa? Lalu, jangan-jangan iya sekalinya saya gagal pada suatu hari, saya enggak bisa survive?" batin saya. Di sisi lain, saya enggak menganggap setiap statement dari orang lain adalah kesempatan untuk berargumen atau ladang untuk adu visi. Ada masanya, saya hanya tersenyum dan berharap obrolan melaju ke arah lain.
"Kalau aku sih, udah biasa gagal. Jadi ya udah, hidup dijalanin aja," lanjut dia.
Sekali lagi, saya mengembangkan senyum.
Lempar waktu ke tujuh tahun kemudian, saat ini, saya rasa baik jadi saya atau dia, sama-sama enggak enak, sih. Ketika yang lain menikmati masa-masa menyenangkan jadi mahasiswa, saya dan dia malah ngobrolin soal kegagalan dan segala macam kata yang sama makna dengannya. Ha-ha-ha. Kiddin!
Kembali serius. Jujur, pada masa itu saya memang takut gagal. Hal yang paling saya takutkan dalam hidup adalah jadi orang gagal. Jadi saya selalu berusaha melakukan segala sesuatu dengan benar. Dua kata yang paling nista dan enggak pernah saya harap ada orang menggunakannya untuk mendeskripsikan saya adalah, enggak kompeten. Ketika itu. Saya punya standar yang tinggi (kadang mungkin kelewat tinggi?) untuk segala sesuatu. Misalnya, waktu itu IPK saya kalau enggak salah 3,7 atau 3,8 dan sempat jadi salah satu mahasiswa dengan IPK tertinggi di angkatannya. Tapi apakah itu membuat saya senang? Biasa aja. Karena waktu itu bagi saya masuk Fikom Unpad adalah kegagalan saya masuk Manajemen Unpad. Belum lagi mantan pacar jaman SMA dulu kuliahnya di ITB. Bukannya enggak bersyukur. Tapi saya selalu melihat ada banyak banget hal keren di sekitar saya yang kemudian saya merasa bukan apa-apa dibandingkan dengannya. Kebayang, dong, pola pikir saya waktu itu seperti apa? Jadi terus terang, kadang saya suka terngiang-ngiang kalimat dari teman saya itu, teman yang sekarang entah di detik ini lagi sibuk ngerjain apa.
Gimana, yah, kalau saya gagal? Maksudnya benar-benar gagal. Bukan gagal-gagal kecil. Gagal yang memang gagal versi semua orang, umum, bukan hanya saya. Yang membuat saya malu bukan kepalang.
Little that I know ternyata manusia itu punya kemiripan dengan kecoak. Dalam artian, bisa bertahan hidup di keadaan seburuk apa pun. Dalam artian, bisa ditimpuk sandal (sandal kehidupan) tapi enggak langsung mati. Dalam artian, dalam keadaan terpojok, dia malah terbang! Dan saya rasa insting kecoak ini tertanam dalam DNA kita. Sehingga ketika mengalami kesulitan atau kegagalan, dengan naluriah kita akan berusaha bertahan hidup. Learn to survive.
Dan ini juga yang terjadi pada saya belum lama ini. Saya gagal. Gagal yang memang gagal dalam artian sebenarnya. Gagal memenuhi standar saya sendiri. Gagal jadi sosok yang saya (dan orang lain) harapkan untuk diri saya sendiri. Gagal menjadi apa yang saya (dan orang lain) percaya. Dan terus terang, ada momen di mana saya merasa enggak akan bisa bangkit. Tepat seperti yang teman saya katakan. Tapi kemudian, seperti kecoak, saya merangkak dengan sisa-sisa tenaga dan kaki yang masih ada.
So we fall.
We bleed.
We feel like we can't make it.
But then, slowly but sure we crawl back to life. It's normal.
It's human.
Wait. Setelah saya pikir-pikir ini enggak banget, deh, menganalogikan diri sendiri dengan kecoak. Cocroach. Panggilan para suku Hutu untuk para suku Tutsi di Rwanda. Karena menurut mereka, sebagai 'kecoak' suku Tutsi ini enggak ada artinya hidup di dunia. Menurut mereka.
Oke, saya mulai melantur.
Kalau boleh saya mencari analogi yang lebih cantik, dibanding kecoak mungkin mendingan bunga teratai, yang belum lama ini memesona saya ketika melihatnya di Ubud. Kita para survivor (atas kegagalan apa pun dalam hidup) adalah bunga teratai. Yang tetap (berusaha) bertumbuh dengan cantiknya walau hidup di air penuh lumpur.
She teach me to rise above from muddy water.
And to detached myself from the storm.
It was only water.
My leaves and petals will be dry still.
As everything will be okay.
Jadi, teman, saya gagal! Dan mungkin ke depannya saya akan gagal lagi. Semoga bukan kegagalan yang sama. Udah ah, ampun, saya lelah.
Saya,
Yang dulu kamu panggil Aciles.


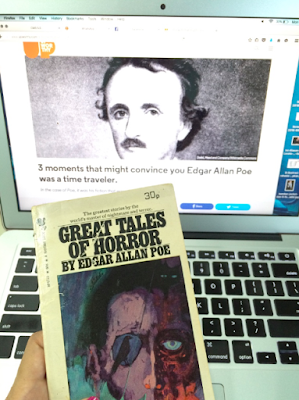

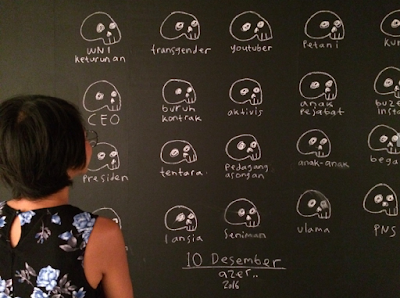
Comments
Post a Comment