Di Usia Berapa Kamu Bangga Jadi Perempuan?
“Ibu, kenapa sih, aku perempuan?” Pernah enggak sih nanya gitu waktu kecil? Waktu kakak laki-laki boleh main sepeda jauh-jauh? Waktu kakak laki-laki enggak dimarahi karena main kotor-kotoran di selokan? Waktu kakak laki-laki gerah dan bajunya dibuka di luar rumah?
Pernah enggak sih dalam hati merasa, “enak, ya, jadi laki-laki?” Waktu kakak laki-laki enggak dimarahi
karena belum pulang kuliah sampai malam bahkan menginap di rumah teman? Waktu
kakak laki-laki enggak dibilang harus bisa masak, pandai nyapu, pinter dandan,
selalu memerhatikan pakaian, senyum dan menyapa tetangga?
Si ujang
Waktu SMP saya pernah dipanggil ‘ujang,’ itu panggilan buat
anak laki-laki di Sunda. Karena rambut saya pendek, pakai baju lungsuran dari
kakak laki-laki, dan suka pakai topi. Selain karena bajunya ada di rumah,
sebenarnya ketika itu saya berharap kalau pakai baju seperti laki-laki, saya
akan punya kebebasan seperti kakak saya, laki-laki. Saya merasa bangga sebagai
perempuan tomboy. Pakai payung itu
perempuan banget, lemah. Kuat itu pakai topi kalau hujan.
Tapi anehnya, saya sedih sekali, ketika bapak itu memanggil
saya ujang. Di situ saya sadar, saya ingin diakui sebagai perempuan.
Masuk SMA saya masih tomboy,
suka pakai celana ngatung, spike belt,
jaket distro yang potongannya lurus warna hitam atau abu. Tapi, rambut saya
panjang dan suka pakai rok pendek ke sekolah. Rujukannya waktu itu, Avril
Lavigne. Seperti banyak remaja perempuan angkatan saya ketika itu. Avril
seperti mengajak kami menggugat stereotype
atas penampilan perempuan, dengan eyeliner
hitam, celana ‘sontog,’ sneakers, dan
topinya. Di awal kemunculannya dia tampak tomboy,
bad ass, cool.
Malah saya juga merasa lebih suka ngumpul sama teman-teman
laki-laki. Sampai ikut touring motor
dan sebangku juga sama laki-laki. Tapi lama-lama kok saya ini seperti enggak
ada bedanya sama teman-teman laki-laki ini, yah? Lalu ketika masa ‘puber,’
pengen kelihatan seperti perempuan, soalnya suka sama laki-laki, ada perasaan
pengen tampil feminine. Tapi hal-hal
yang membuat saya merasa terikat, gender stereotype,
tetap saya tolak.
“Laki-laki kayak apa
yang mau sama perempuan males, bangunnya siang? Perempuan itu harus bangun
pagi, harus rajin.”
“Ya laki-laki yang
males bangun pagi juga, paling.”
Kalimat-kalimat membantah yang malah bikin ibu saya naik
darah macam ini banyak sekali keluar dari mulut. Sebenarnya bukan ingin melawan
ibu, tapi kok saya enggak sepakat sama ide-ide tentang perempuan yang diajarkan
ibu atau orang-orang di sekitar saya ketika itu. Rasa kesal ini kemudian
menyulut amarah, yang tidak terarah, akhirnya saya terlihat seperti
pembangkang.
Belajar jadi
perempuan
“Kamu belajar, dong,
jadi perempuan!” Biasanya kalimat nada kayak gini keluarnya kalau saya
makan dengan satu kaki naik ke kursi atau kalau saya keluar rumah bahkan enggak
bedakan atau sisiran. Setelah ratusan kali mendengar kalimat kayak gini,
sepertinya di jaman kuliah saya baru benar-benar belajar jadi perempuan.
Gara-gara mengerjakan tugas kuliah, saya bertemu feminis
yang dengan tegas bilang dia enggak butuh laki-laki. Saya bertemu transgender perempuan yang
memperjuangkan keamanan dan kesehatan komunitasnya. Saya bertemu musisi
perempuan yang awalnya dipandang sebelah mata lalu dia mendunia. Saya bertemu
pengerajin keset yang bekerja keras demi keluarga.
Saya tertempa kisah
perempuan tokoh dunia, pujangga, dan sutradara yang kesemuanya mengajarkan saya
satu hal, jadi perempuan itu jadi diri sendiri. Tidak ada kewajiban padanya
untuk memenuhi tuntutan dari kanan-kiri. Karena kalau mereka terlalu banyak mendengarkan apa kata orang, mereka enggak
akan jadi sebagaimana mereka yang sekarang, yang mana sangat menginspirasi
saya.
Belajar jadi manusia
Pelajaran berlanjut di dunia professional. Malah, di sini saya semacam naik kelas. Setelah yang
teoritis dan ideal saya pelajari di kampus, di dunia kerjalah saya praktek dan
langsung melihat contoh nyatanya. Apalagi kerja di media lifestyle perempuan, banyak pimpinan perempuan, banyak bertemu
narasumber ahli yang perempuan, juga membahas hal-hal yang terkait perempuan.
Setelah sekian tahun, baru di dunia kerja ‘keputrian’ ini menjadi menyenangkan.
Akhirnya saya paham bahwa untuk mendapatkan kebebasan, saya
enggak harus berpakaian seperti laki-laki. Kalau suka ya silakan, tapi enggak
harus. Saya bisa berlari mengejar Kopaja dengan memakai wedges. Saya bisa wawancara pemain sepakbola sambil mengapit hand bag. Saya bisa menulis artikel
tentang kekerasan terhadap perempuan dengan jari-jari yang diwarnai cat kuku.
Saya paham bahwa untuk jadi cool, saya enggak harus jadi tomboy.
Kalau suka ya silakan, tapi enggak harus. Peduli penampilan bukan berarti
enggak peduli isi otak. Pakai makeup
bukan berarti enggak percaya diri sama kulit sendiri. Banyak perempuan di
bidang fashion atau kecantikan yang smart dan mereka punya suara yang
didengar.
Saya paham bahwa untuk jadi kuat, saya enggak harus bad ass, enggak harus selalu bergaul
dengan laki-laki, enggak harus ngomong kasar. Kalau suka ya silakan, tapi
enggak harus. Inspirasi dan kekuatan bisa datang dari mana saja. Belakangan,
saya belajar banyak menjadi kuat dari perempuan. Para perempuan yang kuat
sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, sebagai pengajar, sebagai anak, sebagai
pemimpi yang begitu keras kepala dengan impiannya.
Di usia 25 ketika itu, saya paham bahwa untuk menjadi
bangga, saya enggak harus merasa ingin diasosiasikan dengan laki-laki atau
ingin berada di kategori yang sama. Kategorinya seharusnya bukan berdasarkan gender. Kategorinya seharusnya adalah
karya, adalah bahagia.






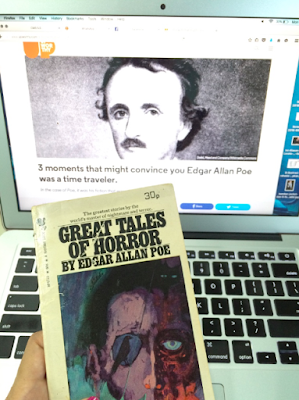

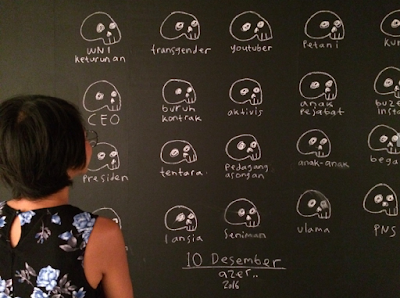
Comments
Post a Comment