Ya elah, hari gini masih nulis soal cinta?
Seperti hidup, emang
iya cinta itu, berkurang seiring usia?
Brett Anderson bilang, loveis dead. Di usia 40-an dia menuliskan lirik dan lagu yang ikut bikin saya
patah hati. Masuk playlist. Masuk
hati. Tapi di tahun 2007 itu, belum benar-benar masuk ke kenyataan sehari-hari
hidup saya. Saya, masih jatuh cinta. Lagu Brett yang satu ini, tiba-tiba saya
ingat lagi setelah lama enggak mendengarkannya lagi. Suatu sore, di suatu
tempat, karena suatu hal. Enggak akan sok misterius, suatu halnya justru yang
akan saya tulis.
Apa iya di usia tertentu, kita akan merasa fed up dan merasa love is dead? Soalnya, term
ini keluar dari orang yang sama yang pernah bilang “you and me all we want to be is lazy,” yang pernah bilang "we'll shine like the morning and sin in the sun oh if you stay." Mungkin berubah jadi bitter karena usia?
Bukan hanya karena Brett sih, sebenarnya. Akhir-akhir ini
banyak ngobrol sama teman-teman yang usianya jauh di atas saya. Mulai dari
delapan, sepuluh, bahkan lebih. Obrolannya macam-macam. Yang seru dan membuka
pikiran, banyak. Yang membuat saya berpikir dewasa itu bukan usia, banyak. Yang
membuat saya merasa usia itu bukan masalah buat pergaulan, juga banyak. Tapi
ada satu tema yang setiap kali muncul, saya ingin pakai ear plug, atau menggali lubang, atau keluar dari TV. Karena rasanya
saya lagi ada di adegan sinetron yang saya enggak mau jadi bagian darinya. Tapi
tetap di sana karena, jujur, penasaran. Tema yang membuat saya kepikiran sama single Brett Anderson tadi.
Apa iya di usia tententu, kita akan merasa fed up dan merasa love is dead? Atau pemahaman saya soal cinta aja yang udah out of date? Atau justru
kekanak-kanakan? Terlalu banyak nonton film? Padahal saya selalu merasa saya
realis. Tidak termasuk ke dalam golongan hopelessly
romantic.
Perceraian.
Perselingkuhan. Pacar selingan. Jajan di jalan. Perdebatan soal uang. Berbagai
pengakuan yang mengejutkan.
Tuh kan, kayak tema sinetron.
Yang seperti ini bukan hal baru, sih. Dulu pun udah sering
mendengar atau melihat langsung. Dan itu juga yang sempat membuat langkah
sedikit (mungkin banyak) tertahan untuk memutuskan menikah. Rasanya, tidak
pernah melihat pasangan yang sudah tua, usia 40 tahun ke atas, happily ever after. Enggak punya role model pernikahan yang langgeng,
tanpa PPPJB di atas.
Tapi ketika tema itu jadi obrolan kasual seakan enggak ada
pihak yang sakit hati, ini baru saya alami. Karena sebelumnya, segala obrolan
yang berhubungan dengan yang seperti ini, cuma terjadi di balik kamar kosan.
Cuma terjadi lewat obrolan mendalam dua orang, di mana keduanya tahu, ini bukan
sesuatu yang begitu saja dibagi. Ada pergolakan. Ada luka. Ada malu. Ada
maklum. Ada air mata.
Di tengah obrolan kasual yang kadang membuat perut mual ini,
saya yang merasa sudah realis, tiba-tiba dalam hati sadar. Sial. Mungkin saya
selama ini hopelessly romantic.
Karena saya masih
ingat.
Bagaimana rasanya duduk berdua tanpa berkata-kata. Jantung
berdegup, ringan di kepala. Senang bukan kepalang, bisa mendengar suara
napasnya. Bisa mencium wangi parfumnya. Terduduk bersama seseorang, yang, dari
semua orang di dunia, maunya cuma sama dia.
Tapi ketika menoleh, barulah terasa, kalau dua jengkal di
sebelah ada seorang pria yang baru saya kenal setengahnya saja. Enggak tahu
sedang merasa apa atau maunya apa. Mulai terasa mulas. Duduk bersebelahan sama
orang asing yang bahkan enggak tahu kenapa dia bilang suka sama saya. Yang
bahkan enggak tahu dia senang atau enggak, karena mukanya ya begitu saja.
Seperti sedang memikirkan sesuatu, enggak tahu apa.
Seperti ingin lari, teriak, kabur, tapi, juga ingin tinggal
dan enggak sabar. Enggak sabar untuk tahu semua tentang dia. Tahu kami mau ke
mana. Enggak sabar untuk duduk berdua tanpa enggak merasa mulas dan pengen
kabur lagi.
Saya mungkin lupa sama banyak detil soal hubungan saya sama
dia. Tapi saya masih ingat, gimana rasanya, lebih dari sepuluh tahun yang lalu,
waktu pertama kenal jauh sama dia.
Makanya.
Kalau ditanya teman kenapa waktu ‘dia nanya itu’ saya jawab “iya,”
saya suka bingung. Karena saya pikir saya realis. Harusnya saya punya jawaban
yang lain. Mau bereproduksi, kek. Mau apa, kek. Tapi kalau boleh jujur, ya
jawabannya cuma itu. Yang kata Brett Anderson udah dead. Yang teman-teman saya mengesankan itu bukan faktor utama. Yang
terlalu gengsi buat saya katakan. Bahkan terlalu gengsi buat saya tulis.
Ya elah, masak saya
harus bilang, “karena cinta?”
Dan bahkan ketika obrolan dengan tema yang membuat buku
kuduk merinding itu berlangsung, saya masih juga percaya. Kalau, mungkin, saya
berbeda. Mungkin kami berbeda. Sepuluh persen pembenaran, 90 persen benar-benar
percaya. Sial. Mungkin saya ini memang hopelessly
romantic.
Tapi mungkin, ini memang sifat dasar manusia, gimana pun
keadaan dan kenyataannya, terus aja menyimpan harap. Dan berpikir kalau, entah
karena apa atau bagaimana, kita ini, berbeda.
**kalau dia baca,
pasti bilang, “jangan terlalu dipikirin nanti gimana. Yang penting berusaha dan
berdoa.” Ya, kan?

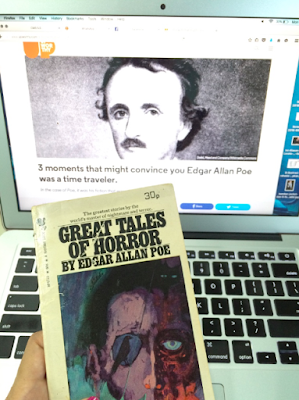

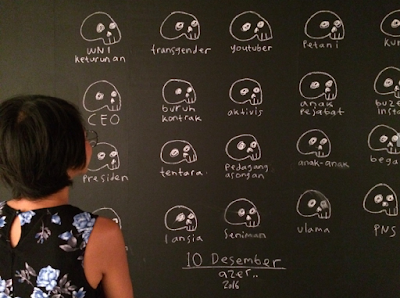
Comments
Post a Comment